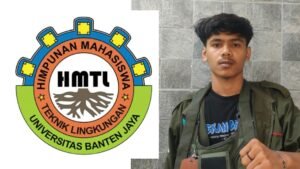Krisis pergerakan yang terjadi di kalangan Mahasiswa Universitas Pamulang, Serang, Banten merupakan fenomena yang mengkhawatirkan. Mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan, bergerak aktif dalam diskusi, menulis, dan turun ke jalan untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran, malah terlihat seolah ‘mati’ dan tidak bergerak sama sekali. Faktor-faktor seperti penyimpangan sosial, kurangnya literasi, serta kemajuan teknologi dan budaya asing, semuanya turut berkontribusi pada masalah ini.
Gerakan mahasiswa yang tampak mati ini tidak hanya disebabkan oleh faktor eksternal saja, tetapi juga oleh kegagalan sistem kampus sebagai agen pendidikan. Sistem kampus yang seharusnya menjadi tempat yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengembangkan wawasan, dan bertindak radikal dalam melawan ketidakadilan, justru jauh dari nilai-nilai pendidikan yang seharusnya menjadi inti dari proses pembelajaran.
Hal ini membuat mahasiswa kehilangan bobot namanya sebagai ‘Mahasiswa’ yang memiliki semangat perubahan.
Saat ini, kita semua menyaksikan betapa krisis pergerakan mahasiswa ini dalam berorganisasi dan bermasyarakat. Mahasiswa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan hak-hak rakyat, menentang korupsi dan ketidakadilan, serta mengusung pemikiran-pemikiran radikal untuk menciptakan perubahan sosial yang nyata. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya. Mahasiswa terjebak dalam pola pikir yang pasif, terpengaruh oleh budaya konsumerisme, hedonisme, dan ebih fokus pada pencapaian pribadi daripada perubahan sosial yang lebih luas.
Kita perlu merenungkan, apakah mahasiswa sepenuhnya harus disalahkan atas fenomena ini? Ataukah sistem pendidikan kita sendiri yang sudah gagal dalam menjalankan peran serta fungsi dengan sebaik-baiknya? Keduanya tentu menjadi faktor.
Pertama, teknologi, budaya luar, dan tren yang mengalihkan perhatian mahasiswa dari perjuangan kolektif menuju pencapaian individu semata. Banyak mahasiswa yang terperangkap dalam arus zaman teknologi dan melupakan bagaimana seharusnya mereka menjadi mahasiswa.
Kedua, kampus yang tidak lagi berperan sebagai rumah bagi mahasiswa untuk belajar dan berkembang secara kritis. Bahkan, kampus tidak mendorong mahasiswa untuk mengikuti berbagai kegiatan organisasi eksternal sebagai pilihan yang mereka minati, yang seharusnya menjadi wadah untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, berdiskusi, dan berorganisasi.
Beberapa dosen memang mengatakan kepada mahasiswanya jika mereka harus berfikir kritis, tetapi hanya sebatas itu. Mereka tidak memberikan metode atau langkah konkret untuk berfikir kritis, tidak mengajarkan tahapan demi tahapan hingga praktiknya. Jika begitu, artinya sama halnya ketika mahasiswa diwajibkan untuk mengikuti e-learning sebagai pengganti pelajaran tatap muka, mereka hanya diminta untuk menjawab beberapa soal tanpa mempertanyakan apakah metode tersebut benar-benar efektif dalam memahami pelajaran atau malah berdampak buruk pada pemahaman yang lebih mendalam. Hal ini terlihat nihil.
Jika tujuan utama sebuah universitas adalah untuk membangun reputasi sebagai institusi pendidikan ternama, maka yang perlu kita soroti bukanlah seberapa banyak mahasiswa yang belajar di sana, tetapi sejauh mana mahasiswa Universitas Pamulang ini bisa meraih prestasi dalam mewujudkan perubahan nyata dalam masyarakat.
Apa saja yang mereka lakukan saat menjadi mahasiswa? Apa saja pencapaian sarjana mereka? Bidang apa yang mereka tekuni setelah lulus? Sebagai contoh, Harvard University mendapatkan pengakuan bukan berdasarkan berapa banyak mahasiswa yang belajar di sana, tetapi berdasarkan berapa banyak mahasiswa atau alumni yang telah menciptakan ide-ide inovatif, menulis karya yang menjadi sumber inspirasi, sehingga membuat nama mereka dikenal di seluruh dunia.
Harvard University telah menghasilkan banyak lulusan yang menjadi tokoh penting di berbagai bidang, termasuk politik, bisnis, seni, teknologi dan ilmu pengetahuan. Prestasi individu itulah yang sebenarnya mencerminkan kualitas sebuah universitas. Namun, di Universitas Pamulang, kita jarang melihat mahasiswa yang mampu menonjolkan dirinya dengan ilmu yang telah ia dapat di universitas ini, atau mencapai prestasi yang signifikan. Kita perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa hal ini terjadi? Apakah karena kurangnya dorongan dan dukungan dari sistem pendidikan yang disebutkan tadi?
Beberapa mahasiswa mungkin berfikir “Saya benar benar buruk karna tidak bergerak di bidang organisasi, berdiskusi, menulis bahkan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat,” tapi dengan “senang rasanya bahwa yang seperti itu bukan hanya saya”. Fakta bahwa mereka sadar apa yang seharusnya mereka lakukan tetapi memilih tidak melakukannya adalah pertanda bahwa kita sebagai bangsa sedang berada dalam krisis moral. Mahasiswa seharusnya menjadi pionir dalam perubahan sosial, bukan hanya belajar untuk diri sendiri, tetapi juga berjuang untuk hak-hak mereka serta hak-hak masyarakat yang lebih luas. Mahasiswa harus berani berbicara dengan lantang, mengkritik kinerja pemerintah, dan menuntut perubahan yang nyata.
Oleh karena itu, penting bagi kita semua, termasuk mahasiswa, untuk kembali pada nilai-nilai pendidikan dan moral yang sejati. Mahasiswa harus berani bergerak secara kritis dan radikal, mengambil peran aktif dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, dan perubahan sosial yang lebih baik. Hanya dengan melakukan itu, generasi muda kita akan menjadi harapan cerah bagi masa depan bangsa.
Sampai pada titik ini, kita melihat bahwa krisis pergerakan mahasiswa di Universitas Pamulang adalah sebuah fenomena yang sangat mengkhawatirkan. Faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, seperti penyimpangan sosial, kurangnya literasi, dan pengaruh budaya asing, semuanya berperan dalam menghambat pergerakan mahasiswa.
Penyimpangan sosial, seperti tindakan korupsi dan ketidakadilan yang masih merajalela di masyarakat, membuat mahasiswa merasa terbebani dan sulit untuk bergerak. Kurangnya literasi juga menjadi kendala, karena mahasiswa yang minim pengetahuan dan pemahaman tentang isu-isu sosial dan politik cenderung menjadi pasif dan tidak berperan dalam perubahan.
Selain itu, kemajuan teknologi dan budaya asing juga memberikan dampak negatif pada pergerakan mahasiswa. Mahasiswa terjebak dalam budaya konsumerisme yang mengutamakan keinginan pribadi dan pencapaian materi, sehingga mengabaikan perjuangan kolektif untuk keadilan dan perubahan sosial. Kemajuan teknologi juga membuat mahasiswa lebih fokus pada media sosial dan hiburan digital, hanya dengan berbaring mereka dapat menghibur dirinya dan nyaman dengan itu daripada mengambil tindakan nyata di dunia nyata.
Namun, tidak hanya faktor eksternal yang berkontribusi pada krisis pergerakan mahasiswa. Sistem pendidikan juga memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan semangat perubahan mahasiswa. Sayangnya, sistem pendidikan kita sering kali gagal dalam memberikan pendidikan yang mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, mengembangkan wawasan, dan bertindak radikal. Kurikulum yang terlalu teoretis dan kurangnya pendekatan praktis dalam pembelajaran membuat mahasiswa kehilangan minat dan semangat untuk bergerak.
Kurangnya dukungan dan dorongan dari pihak kampus menjadi faktor utama yang perlu kita soroti. Kampus seharusnya menjadi tempat yang menyediakan ruang dan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan kepemimpinan, berdiskusi, dan berorganisasi. Namun, seringkali mahasiswa diabaikan dan tidak didorong untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi yang ada demi kepentingan kampusnya sendiri. Ini mengakibatkan mahasiswa kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri dan memperjuangkan perubahan yang mereka inginkan.
Dalam mengatasi krisis pergerakan ini, perlu adanya langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan oleh semua pihak terkait. Pihak kampus harus mendorong dan memberikan dukungan yang lebih besar kepada mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi dan pengembangan diri.
Selain itu, sistem pendidikan juga perlu diperbaiki dengan memperkuat pendekatan praktis dalam pembelajaran, serta memberikan pelatihan dan bimbingan yang lebih baik dalam mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan berpikir kritis.
Mahasiswa juga perlu mengambil inisiatif dan bertanggung jawab atas pergerakan mereka sendiri. Mereka harus berani berbicara dengan lantang, mengkritik ketidakadilan, dan menuntut perubahan yang nyata. Mahasiswa juga perlu meningkatkan literasi dan pemahaman mereka tentang isu-isu sosial dan politik, agar dapat berperan aktif dalam memperjuangkan keadilan dan perubahan sosial.
Dalam menghadapi krisis pergerakan mahasiswa, kita semua harus menyadari bahwa perubahan tidak akan terjadi dengan sendirinya. Diperlukan upaya kolektif dan komitmen yang kuat dari semua pihak terkait untuk menciptakan perubahan. Mahasiswa harus menjadi agen perubahan yang aktif dan berani, sementara pihak kampus dan sistem pendidikan harus memberikan dukungan dan lingkungan yang kondusif bagi pergerakan mahasiswa, baik internal maupun eksternal. Hanya dengan kerjasama dan komitmen bersama, kita dapat mengatasi krisis pergerakan mahasiswa dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bangsa ini.(*)