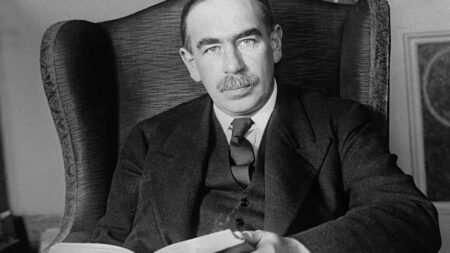BANTENCORNER.COM – Di tengah hiruk pikuk kampus modern, di mana layar laptop bersinar terang dengan data akreditasi dan notifikasi rapat tak henti, kita sering lupa bahwa universitas sebenarnya adalah perjalanan pulang. Bukan pulang ke asal fisik, tapi ke esensi pengetahuan itu sendiri. ke ruang di mana ilmu bukan sekadar komoditas, melainkan jembatan menuju makna dan nurani.
Kampus di antara data dan makna
Ruang kuliah kini tak lagi sepi. Ada bunyi ketikan laptop, notifikasi pesan dari grup kerja, dan pengingat rapat daring yang muncul di tengah penjelasan dosen. Di papan tulis, teori masih diajarkan. Di layar, data tentang akreditasi diperbarui. Di antara keduanya, universitas berdiri di persimpangan antara ilmu sebagai pencarian makna dan ilmu sebagai komoditas.
Kampus yang seharusnya menjadi tempat berpikir bebas, perlahan berubah menjadi pabrik administrasi. Kita menulis bukan untuk memahami, tapi untuk memenuhi. Setiap penelitian dihitung, setiap dosen diawasi, setiap aktivitas harus tercatat di sistem. Namun, semakin banyak data terkumpul, semakin terasa ada yang tak terukur, ruh pengetahuan itu sendiri.
Dari Nalanda ke Universitas modern
Dalam The Golden Road: How Ancient India Transformed the World (2025), William Dalrymple menceritakan kembali masa ketika universitas bukan sekadar lembaga, tapi perjalanan spiritual intelektual. Ia menulis tentang Nalanda, pusat pembelajaran kuno di India, tempat para pelajar dari berbagai negeri menimba ilmu bukan demi pangkat, melainkan demi pencerahan.
“Indian mathematics… first passed from India to Abbasid Baghdad… where they began translating the Sanskrit scientific classics into Arabic. This established… a revolutionary Indian concept that would transform mathematics: zero.” (Dalrymple, 2025, p. 26–27)
Dari nol, dunia belajar tentang nilai dan logika, tentang makna dari ketiadaan yang justru melahirkan segalanya. Namun Dalrymple mengingatkan bahwa yang membuat ilmu berkembang bukan sekadar kecerdasan, melainkan keikhlasan untuk belajar dan berbagi. Di Nalanda, ilmu adalah jalan pengabdian, bukan jalan menuju jabatan.
Kini, universitas modern tampak jauh dari semangat itu. Kita mengukur mutu pendidikan dari peringkat internasional, bukan dari kedalaman dialog. Kita sibuk menata laporan, tapi lupa menata cara berpikir. Seolah ilmu hanya berharga ketika memiliki nilai tambah ekonomi, bukan nilai kemanusiaan.
Luka Sunyi Dunia Akademik
Peter Fleming, dalam Dark Academia: How Universities Die (2021), mengingatkan dengan getir bahwa universitas masa kini “menghasilkan manusia yang terluka.”
“If large formal institutions encourage certain types of selfhood, a rudimentary insight of organisational sociology, then higher education today is undoubtedly producing damaged people.” (Fleming, 2021, p. 22)
Kata damaged di sini bukan tentang kerusakan fisik, tapi keretakan batin akademik. Ketika dosen dan mahasiswa kehilangan keutuhan dirinya. Dosen mengejar angka kredit, mahasiswa mengejar nilai, dan keduanya sama-sama kelelahan di bawah tekanan sistem yang menuntut efisiensi tanpa memberi ruang bagi refleksi. Ilmu kehilangan kedalaman karena terlalu sering dipaksa menjadi laporan.
Birokrasi kampus berkembang cepat, tetapi manusia di dalamnya justru berjalan di tempat. Sementara itu, ketimpangan yang halus terus tumbuh, antara dosen tetap dan kontrak, antara yang diakui dan yang diabaikan, antara regulasi yang kaku dan kenyataan yang luwes. Beberapa akademisi muda berjuang melanjutkan studi dengan beasiswa, membawa harapan untuk memperkaya lembaga, namun justru dihadapkan pada sistem yang belum sepenuhnya tahu cara merangkul mereka.
Ketiadaan kebijakan yang jelas sering melahirkan standar ganda, hak dan kewajiban berjalan di jalur yang tak selalu seimbang. Regulasi bergerak lebih cepat daripada kebijakan yang berpihak pada manusia. Dalam diam, kampus menumbuhkan sejenis keletihan struktural, letih karena mencintai ilmu, tapi tak tahu harus mencintai dalam bentuk apa.
Menyisakan ruang untuk Nurani
Akreditasi dan tata kelola tentu penting. Mereka menjaga universitas dari kekacauan dan memastikan standar mutu. Namun, di banyak tempat, sistem itu berubah menjadi ritual administratif tanpa jiwa. Kita sibuk mempercantik dokumen, tapi tak sempat memperindah nalar. Ilmu yang seharusnya lahir dari keingintahuan, kini terjebak dalam logika proyek.
Dalam suasana seperti ini, keberanian berpikir perlahan surut. Kritik dianggap gangguan, refleksi dianggap pemborosan waktu. Padahal, universitas tidak akan maju dengan kepatuhan, tapi dengan keberanian intelektual. Keberanian untuk mempertanyakan, untuk salah, untuk berbeda.
Dalrymple dan Fleming sebenarnya berbicara tentang hal yang sama dari dua ujung sejarah: yang satu tentang “peradaban yang tumbuh karena kebebasan belajar”, yang lain tentang “peradaban yang meredup karena ketakutan pada kebebasan itu sendiri.” Keduanya mengingatkan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa tumbuh dalam tekanan, karena tekanan melahirkan kepatuhan, bukan pemahaman.
Mungkin universitas perlu belajar kembali dari makna “nol” yang ditulis Dalrymple, ruang kosong yang penuh potensi. Kampus memerlukan ruang semacam itu. Ruang bagi dosen untuk berpikir tanpa dikejar laporan. Ruang bagi mahasiswa untuk salah tanpa dihukum nilai. Ruang bagi lembaga untuk menumbuhkan manusia, bukan hanya mencetak data.
Karena pada akhirnya, pendidikan tinggi bukan soal gedung megah atau ranking tinggi, melainkan tentang keadilan dalam pengetahuan dan keikhlasan dalam mencari kebenaran. Dan ketika nurani kembali menjadi bagian dari struktur, universitas akan menemukan kembali jalan pulangnya: dari birokrasi menuju kebijaksanaan, dari sistem menuju kemanusiaan