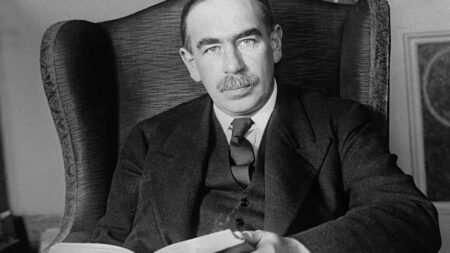BANTENCORNER.COM-Partai politik sejak awal dirancang sebagai jantung demokrasi. Ia hadir bukan hanya sebagai wadah untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, tetapi juga sebagai mekanisme rekrutmen kepemimpinan politik yang sah. Namun, dalam konteks Indonesia, partai politik kerap menjadi sorotan publik bukan karena prestasinya dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, melainkan karena praktik-praktik yang lebih menonjolkan kepentingan elite partai dan kepemimpinan internal yang sulit keluar dari pola lama. Pertanyaan besar pun muncul: apakah partai politik di Indonesia benar-benar bekerja untuk rakyat, ataukah sekadar menjadi instrumen bagi elite yang terjebak dalam kebiasaan lama?
Partai Politik sebagai Wadah Aspirasi: Ideal dan Realitas
Secara normatif, Undang-Undang Partai Politik menegaskan bahwa fungsi utama partai adalah sebagai sarana pendidikan politik, penyerap aspirasi masyarakat, penyusun kebijakan, serta perekrut pemimpin. Dalam teori politik, partai ibarat jembatan antara rakyat dengan negara, memastikan suara masyarakat terartikulasi dalam kebijakan publik.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan jurang yang lebar. Partai-partai sering kali hanya aktif menjelang pemilu, dengan aktivitas utama berupa kampanye yang sarat jargon populis. Setelah pemilu usai, kedekatan dengan rakyat meredup, berganti dengan konsentrasi pada negosiasi kekuasaan, perebutan kursi menteri, atau pembagian sumber daya politik. Akibatnya, kepercayaan publik terhadap partai politik menurun drastis.
Survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2025 mencatat partai politik menempati posisi terbawah dalam tingkat kepercayaan publik, hanya 4 persen yang sangat percaya, sementara 30 persen menyatakan kurang percaya. Survei serupa pada September 2024 juga menunjukkan kepercayaan terhadap parpol hanya 51 persen. Angka ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa partai politik belum sepenuhnya mampu menjalankan fungsinya sebagai penghubung rakyat dan negara.
Kepemimpinan yang Terjebak dalam Kebiasaan
Salah satu masalah mendasar partai politik di Indonesia adalah kultur kepemimpinan yang masih sangat personalistik dan oligarkis. Banyak partai digerakkan oleh figur tunggal, baik itu ketua umum, tokoh pendiri, atau bahkan keluarga tertentu. Pergantian kepemimpinan jarang berlangsung secara demokratis; lebih sering ia diwariskan atau ditentukan lewat mekanisme tertutup.
Kebiasaan ini melahirkan dua problem. Pertama, proses kaderisasi menjadi mandek karena potensi kader muda sulit muncul di tengah dominasi elite lama. Kedua, kebijakan partai lebih sering merefleksikan kepentingan kelompok kecil dibanding kepentingan luas masyarakat. Akibatnya, partai menjadi “kendaraan politik pribadi” ketimbang institusi publik.
Fenomena politik dinasti di sejumlah daerah juga memperkuat kritik ini. Partai politik bukan lagi membuka kesempatan seluas-luasnya bagi rakyat untuk masuk dalam arena politik, melainkan hanya mengulang pola pewarisan kekuasaan dari satu keluarga ke keluarga lain. Situasi ini menciptakan kesan bahwa politik adalah arena tertutup, bukan ruang terbuka bagi kompetisi gagasan.
Antara Kepentingan Rakyat dan Kepentingan Elite
Ketika kepentingan elite lebih menonjol, rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Aspirasi masyarakat kerap hanya dijadikan alat untuk meraih simpati dalam kampanye, namun jarang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang berpihak. Banyak kebijakan publik dihasilkan lebih karena pertimbangan politik jangka pendek, misalnya menjaga koalisi atau menyenangkan mitra politik ketimbang benar-benar merespons kebutuhan rakyat.
Contoh sederhana bisa dilihat dalam pembahasan undang-undang strategis yang kerap dilakukan terburu-buru, dengan minim partisipasi publik. Proses legislasi sering kali dipengaruhi oleh transaksi politik di parlemen, bukan hasil dialog mendalam dengan masyarakat sipil. Padahal, keputusan yang lahir di ruang parlemen seharusnya mencerminkan suara rakyat, bukan sekadar kompromi elite.
Tak heran bila kritik keras sering datang dari tokoh politik nasional. Anies Baswedan, menegaskan bahwa banyak partai kini “tersandera oleh kekuasaan”. Ia bertanya, “Kalau masuk partai, pertanyaannya partai mana yang sekarang tidak tersandera oleh kekuasaan… jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam.” Kritik semacam ini menegaskan bahwa publik maupun elite sendiri menyadari betapa dalamnya problem struktural yang menggerogoti parpol.
Tantangan Pelembagaan Partai Politik
Kondisi tersebut memperlihatkan betapa lemahnya pelembagaan partai politik di Indonesia. Pelembagaan partai seharusnya membuat partai berfungsi secara konsisten, transparan, dan demokratis, terlepas dari siapa pemimpinnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya: ketika figur kuat dalam partai melemah atau lengser, partai ikut goyah.
Pelembagaan juga lemah dalam hal pendanaan. Banyak partai bergantung pada sumbangan donatur besar, yang kemudian memengaruhi arah kebijakan. Ketergantungan ini semakin menjauhkan partai dari rakyat, karena prioritasnya lebih diarahkan untuk memenuhi kepentingan para penyandang dana.
Selain itu, mekanisme internal partai masih tertutup. Proses seleksi calon legislatif, misalnya, sering ditentukan oleh loyalitas kepada pemimpin partai ketimbang kapasitas dan integritas calon. Hal ini mempersempit kesempatan bagi kader-kader potensial untuk muncul dan berkontribusi.
Harapan untuk Perubahan
Meski menghadapi banyak tantangan, bukan berarti perbaikan tidak mungkin dilakukan. Ada sejumlah langkah yang dapat menjadi jalan keluar. Pertama, reformasi internal partai harus menjadi prioritas, terutama dalam hal demokratisasi kepemimpinan dan transparansi pendanaan. Kedua, kaderisasi harus dijalankan secara sistematis dan berkelanjutan agar muncul generasi pemimpin politik yang lebih segar dan berintegritas.
Ketiga, masyarakat sipil juga harus lebih kritis dalam mengawasi partai politik. Tekanan publik melalui media, lembaga swadaya masyarakat, maupun gerakan mahasiswa dapat mendorong partai agar lebih akuntabel. Keempat, regulasi negara perlu diperkuat, misalnya dengan memberikan insentif bagi partai yang menerapkan demokrasi internal atau sanksi bagi yang terbukti hanya menjadi kendaraan politik pribadi.
Selain itu, pendidikan politik bagi masyarakat perlu diperluas. Kesadaran politik warga akan memperkuat posisi rakyat dalam menuntut akuntabilitas partai. Jika masyarakat hanya pasif, elite partai akan semakin bebas memainkan agenda mereka sendiri. Sebaliknya, rakyat yang kritis dan aktif bisa menjadi penekan moral agar partai tidak lagi terjebak dalam kebiasaan lama.
Partai politik adalah pilar utama demokrasi, namun kondisinya di Indonesia masih jauh dari ideal. Alih-alih menjadi instrumen untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, banyak partai terjebak dalam pola kepemimpinan lama yang oligarkis dan personalistik. Kebiasaan ini bukan hanya menghambat kaderisasi, tetapi juga mereduksi demokrasi menjadi sekadar prosedural.
Pertanyaan dalam judul tulisan ini—antara kepentingan rakyat dan kepentingan kepemimpinan yang terjebak dalam kebiasaan—sesungguhnya menggambarkan dilema besar demokrasi Indonesia. Jawabannya akan sangat ditentukan oleh keberanian partai politik melakukan reformasi internal dan kesediaan mereka menempatkan rakyat sebagai pusat perjuangan, bukan sekadar alat legitimasi. Jika tidak, maka partai politik akan semakin kehilangan relevansi, dan demokrasi kita akan terus berjalan pincang.***