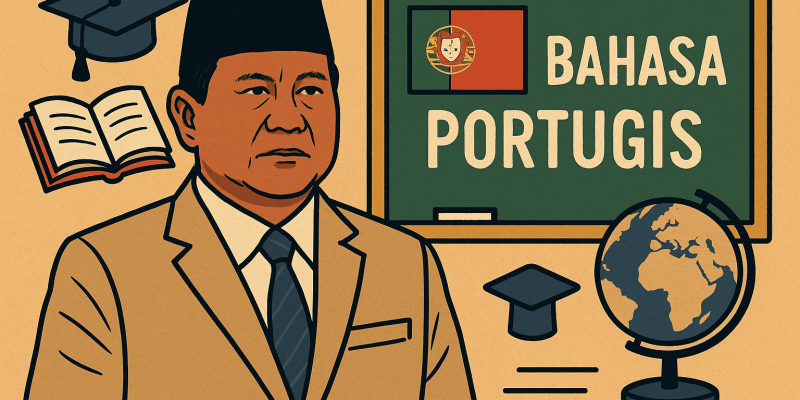Pada 23–24 Oktober kemarin, Presiden Prabowo mengumumkan keputusan yang lumayan mengejutkan, katanya, bahasa Portugis akan dimasukkan sebagai salah satu bahasa prioritas yang diajarkan di sistem pendidikan kita. Pernyataan itu disampaikan saat kunjungan kenegaraan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva ke Jakarta dan ceritanya ini dikaitkan oleh pemerintah sebagai upaya mempererat hubungan strategis Indonesia – Brasil serta memperluas daya saing internasional anak-anak Indonesia.
Formalnya, tercatat dalam sejumlah laporan media nasional dan internasional yang menyingkap bahwa keputusan itu bersifat instruksi presiden untuk menjadikan Portugis setara dengan bahasa-bahasa asing lain yang selama ini diprioritaskan, seperti Inggris, Arab, Mandarin, Jepang, Korea, Prancis, Jerman, dan juga Rusia.
Pernyataan itu, jika dibaca sekilas, dapat dipahami sebagai upaya diplomatik dan ekonomis, bahwa Brasil adalah salah satu negara besar di belahan selatan, anggota BRICS yang punya potensi kerja sama di bidang perdagangan komoditas, energi, dan teknologi agrikultur. Tapi jika dianalisis lebih jauh, terutama dari sudut kebijakan pendidikan, keputusan “sepihak” untuk “menjadikan bahasa Portugis prioritas” menimbulkan serangkaian pertanyaan praktis, pedagogis, anggaran, dan politik yang belum dijawab.
Pertama, perlu dipahami bahwa memasukkan sebuah bahasa ke dalam kurikulum nasional bukan hanya soal keputusan simbolik, tapi juga menuntut kurikulum yang jelas (tingkatan, kompetensi yang diharapkan), guru yang terlatih, materi ajar, pelatihan tenaga pengajar, standar penilaian, serta alokasi anggaran jangka menengah dan panjang. Dari berbagai sumber berita, mengindikasikan perintah itu datang sebagai arahan presiden, sementara kementerian terkait masih diminta untuk “mengatur teknisnya”, celah eksekusional yang rentan menimbulkan ketimpangan implementasi antar-distrik dan daerah.
Kedua, soal prioritas anggaran, kebijakan ini muncul dalam konteks yang lebih besar, yakni kebijakan anggaran pendidikan di era pemerintahan Prabowo yang, menurut media-media internasional, sedang mengalami prioritisasi ulang anggaran yang menimbulkan protes pelajar dan kekhawatiran tentang pembiayaan perguruan tinggi. Financial Times dan laporan-laporan lain mencatat adanya kontroversi publik terkait alokasi besar untuk program lain yang diklaim berdampak pada pemotongan beberapa pos pendidikan tinggi.
Di tengah narasi itu, meluncurkan program bahasa baru nasional membutuhkan bukti bahwa manfaatnya sebanding dengan biaya yang harus disiapkan, misalnya dari pelatihan guru sampai pengadaan bahan ajar, dan bukan hanya manuver diplomatik yang prioritasnya bersifat simbolis. Tanpa kajian dampak biaya-manfaat yang transparan, risiko terjadinya beban tambahan pada sekolah-sekolah yang sudah kekurangan tenaga dan fasilitas menjadi nyata.
Reaksi politik dan akademis terhadap inisiatif ini juga beragam dan saya kira patut juga dicermati. Misalnya, Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyambut gagasan ini bisa memperkaya kompetensi bahasa asing namun menuntut penjelasan manfaat konkret bagi para siswa, pertanyaan tentang “untuk siapa dan untuk apa” diajukan karena kurikulum seharusnya melayani kepentingan pembelajaran dasar, ketahanan budaya, dan kesiapan kerja.
Di sisi birokrasi, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengajaran bahasa asing bertujuan mempermudah komunikasi internasional dan membuka peluang kerja di luar negeri, namun penjelasan teknis tentang tahap pelaksanaan, misalnya apakah Portugis akan diajarkan mulai SD, SMP, atau SMA? apakah sebagai muatan lokal atau muatan nasional? dan bagaimana kaitannya dengan muatan bahasa daerah) ini belum diuraikan secara rinci. Ketidakjelasan ini membuka peluang multitafsir yang berbahaya:, apakah ini bersifat mandatory (wajib) atau optional (pilihan)? Apakah seluruh sekolah akan diwajibkan atau hanya sekolah tertentu dengan kapasitas sumber daya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu perlu segera dijawab.
Dari perspektif pedagogis, ada sejumlah prinsip yang sebaiknya dipenuhi sebelum menambahkan mata pelajaran baru pada skala nasional, yaitu relevansi terhadap kurikulum nasional kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, kesinambungan pembelajaran lintas jenjang, pengembangan kompetensi 4C (critical thinking, creativity, collaboration, communication), dan kemampuan memberikan manfaat nyata kepada peserta didik di pasar tenaga kerja domestik maupun internasional.
Bahasa adalah alat komunikasi dan budaya, memperkenalkan bahasa baru bisa sangat berguna jika disertai program pertukaran, kesempatan beasiswa, dan hubungan ekonomi yang memungkinkan lulusan menggunakan kemampuan itu. Namun memperkenalkan bahasa Portugis semata atas nama diplomasi tanpa roadmap peningkatan kapasitas lokal berisiko hanya menjadi “gimmick” politik, menjadi kebijakan yang lebih menguntungkan citra hubungan bilateral daripada manfaat praktis bagi murid dan guru di berbagai daerah.
Pertimbangan kedaerahan dan keberagaman saya kira juga penting. Indonesia adalah negara dengan pluralitas bahasa dan tantangan pemerataan pendidikan, terlau banyak sekolah di daerah tertinggal masih kekurangan guru bahasa Inggris sendiri, apalagi bahasa asing lainnya. Menjadikan Portugis prioritas nasional tanpa strategi komprehensif untuk memperkuat kapasitas guru bahasa lokal dapat memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.
Selain itu, ada tambahan pertanayaan normatif, bagaimana kebijakan ini sejalan dengan upaya melestarikan bahasa daerah dan memperkuat kompetensi Bahasa Indonesia? Tentunya, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa penambahan bahasa asing tidak mengorbankan pengajaran literasi dasar, pendidikan kewarganegaraan, dan modal budaya nasional. Dokumen kebijakan pendidikan terdahulu menekankan pengembangan karakter dan identitas kebangsaan, intervensi baru harus selaras dengan itu, bukan malah bertentangan.
Dari sisi geopolitik dan ekonomi, argumen pendukung cukup jelas dan mungkin bisa dimaklumi, bahwa mempererat hubungan dengan Brasil (negara besar di Amerika Selatan) bisa membuka jalan bagi kerja sama di sektor komoditas, pertanian, dan investasi. Bahasa Portugis adalah lingua franca di Brasil, Angola, Mozambik, dan beberapa negara Afrika lainnya, menguasai Portugis mungkin membuka jaringan kerja dan nilai tambah tertentu. Namun kebijakan luar negeri yang baik biasanya memiliki landasan domestik yang kuat, misalnya strategi implementasi yang jelas, perjanjian bilateral yang memfasilitasi mobilitas tenaga kerja atau program beasiswa, serta kemitraan akademik untuk menghasilkan materi ajar dan pelatihan guru.
Namun hingga saat ini, liputan berita menunjukkan inisiatif ini lebih berupa instruksi awal daripada kebijakan terpadu yang dilengkapi MoU teknis dan anggaran implementasi. Tanpa itu, klaim manfaat ekonomi tetap bersifat spekulatif.
Singkatnya, wacana memasukkan bahasa Portugis ke sekolah-sekolah Indonesia bisa dimaknai positif jika diterjemahkan menjadi program jangka panjang yang jelas, berbiaya terukur, dan berpihak pada pemerataan kualitas pendidikan. Namun bila kebijakan hanya berhenti pada pengumuman politik tanpa roadmap implementasi, evaluasi kebutuhan, dan keterlibatan pengajar serta pengawas secara substantif, maka kemungkinan besar kebijakan itu akan melahirkan lebih banyak masalah administrasi dan ketimpangan daripada manfaatnya.
Yang mendesak sekarang adalah transparansi, kita berhak mengetahui skema implementasi (tingkatan sekolah mana, apakah wajib atau pilihan, sumber anggaran, target kompetensi, serta indikator evaluasi), kajian biaya-manfaat yang independen, dan rencana pelatihan guru yang nyata. Hanya dengan itu wacana diplomasi kultural ini bisa berubah menjadi kebijakan pendidikan yang benar-benar memperkaya kapasitas generasi muda,bukan sekadar headline hubungan bilateral.
Jika publik dan pemangku kepentingan pendidikan ingin bergerak lebih jauh dan ceritanya mau diseriusin, langkah konkret yang layak diperjuangkan adalah: permintaan kepada Kemdikbudristek untuk mempublikasikan dan membuka konsultasi publik atas rencana tersebut; penugasan kajian akademis independen tentang dampak pembelajaran Portugis di Indonesia; pilot project terbatas pada sekolah yang memiliki kapasitas dan kemitraan bilateral; serta alokasi anggaran terpisah agar tidak mengganggu layanan pendidikan dasar dan literasi. Tanpa langkah-langkah semacam ini, kebijakan yang tampak menjanjikan pada tingkat diplomasi berisiko menjadi beban baru bagi sistem pendidikan yang sedang bergulat dengan tantangan akses, kualitas, dan pemerataan.